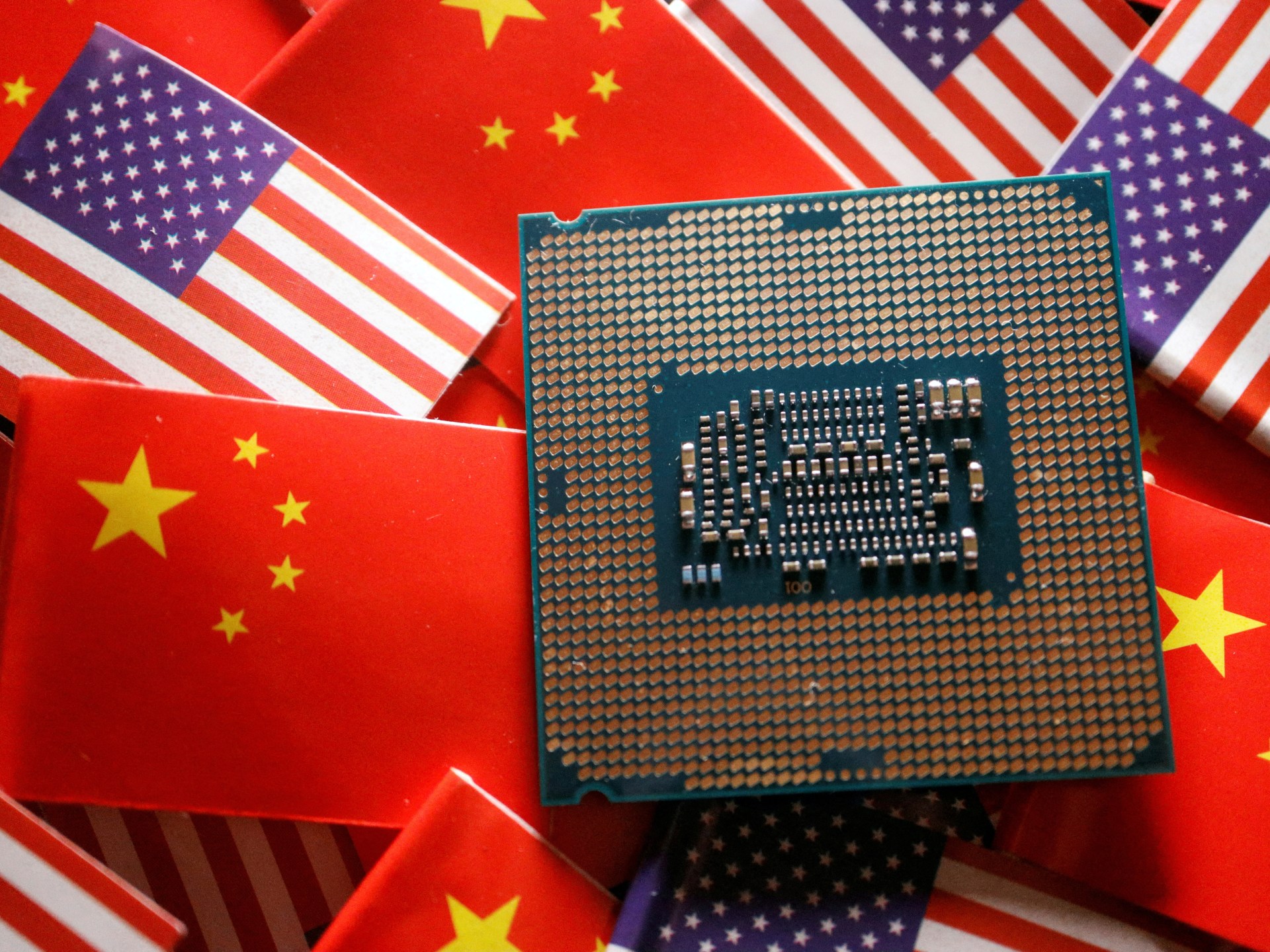Tunisia, Tunisia – Ketakutan bercampur dengan pengunduran diri di stasiun louage Sfax, titik persiapan taksi bersama yang menghubungkan Tunisia.
Antrean panjang dan tidak bergerak untuk melarikan diri dari kota terdiri dari perwakilan dari sebagian besar sub-Sahara Afrika. Banyak yang telah mengalami kesulitan yang hebat dalam perjalanan panjang dan berbahaya mereka ke Tunisia. Sekarang, setelah pertengkaran dengan seorang pria setempat berubah menjadi mematikan, mereka melarikan diri dari Sfax karena takut akan nyawa mereka.
Mengingat sifat migrasi tidak teratur, tidak ada yang bisa mengatakan jumlah migran Afrika yang tidak berdokumen, baik di Tunisia maupun di Sfax. Namun, tampaknya tak terbantahkan bahwa jumlah mereka terus meningkat.
Kematian pria itu pada hari Senin selama pertempuran dengan migran kulit hitam di kota itu tampaknya telah menyulut kertas sentuh yang telah lama membara di kawasan itu, memicu bentrokan antara penduduk dan migran yang digambarkan oleh seorang penonton pada Selasa pagi sebagai “seperti perang saudara”.
Penangkapan berikutnya atas tiga pria dari Kamerun atas pembunuhan tersebut – dan penahanan 34 orang lainnya atas tuduhan memasuki negara itu secara ilegal – tidak banyak menenangkan suasana hati banyak orang di kota yang berfokus pada balas dendam.
Banyak yang ditangkap dalam semalam dan ditempatkan di bus sebelum diantar ke tempat yang dikatakan Human Rights Watch dikatakan sebagai perbatasan militer antara Tunisia dan Libya. Ada pria, wanita, dan bahkan anak-anak yang tersisa untuk menahan panas yang menyengat sambil menunggu semacam solusi.
Bersembunyi di bawah panji, putus asa untuk melarikan diri dari panasnya hari, Muhammad dari Sierra Leone berdiri di pinggir jalan dengan tiga orang lainnya, seluruh harta duniawi mereka di ransel di kaki mereka. Dia melakukan perjalanan melalui Libya yang dilanda kekacauan dan menemukan dirinya ditangkap dan ditebus oleh kelompok bersenjata di sana, sebelum berakhir di Sfax.
“Saya kehilangan kedua orang tua dan saudara laki-laki saya di Sierra Leone,” katanya. “Kekerasan di sini sangat keras. Anak laki-laki Tunisia, mereka datang dan mendobrak pintu dan memaksa masuk. Mereka memukuli saya dan memaksa kami. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan pergi ke Eropa.”
Mohammed berkata bahwa pada malam sebelumnya, sekelompok anak laki-laki Tunisia menyerang dia dan teman-temannya.
“Mereka memukuli kami dengan parang,” jelasnya sambil menunjuk ke lengan temannya yang diperban, yang darahnya masih merembes.

Sentimen publik dan pemerintah
Pengalaman Muhammad sama sekali tidak unik. Ini menemukan gema yang hampir sempurna di antara ratusan migran Afrika yang tidak berdokumen yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka dan sekarang hidup kasar di jalanan.
Sebagian besar hidup damai di Tunisia sebelum Presiden Kais Saied pidato rasis Februari lalu, di mana dia berbicara tentang “gerombolan migran gelap dari Afrika sub-Sahara” yang datang ke Tunisia, membawa serta “semua kekerasan, kejahatan, dan praktik yang tidak dapat diterima”.
Upaya selanjutnya untuk mengecilkan nada diskriminatif dari pidato tersebut sebagai a “salah paham” berbuat banyak untuk membalikkan sentimen publik. Di Sfax khususnya, kekhawatiran tentang kekurangan pangan, ekonomi Tunisia yang merosot dan pengangguran yang mengakar semuanya memicu ketidakpercayaan terhadap orang-orang dari Afrika sub-Sahara, sekaligus berkontribusi pada eksodus Tunisia dari negara kelahiran mereka.
Ketika keadaan keuangan Tunisia memburuk, kehadiran begitu banyak migran Afrika tanpa dokumen menjadi penyelamat bagi segelintir orang terpilih. Dengan sedikit uang di tangan, dan memiliki desakan putus asa untuk mencapai Eropa, para migran sub-Sahara terbukti menjadi pelanggan ideal bagi banyak penduduk setempat yang tinggal di sepanjang garis pantai Sfax, yang sekarang mencari nafkah dengan mengelas perahu-perahu datar kecil yang akan semoga membawa kargo manusia mereka dalam perjalanan satu arah ke Eropa.
Dengan tarif individu sekitar 3.000 dinar Tunisia ($ 970) dan jumlah penumpang hingga 38 per kapal, keuntungan finansial sangat besar bagi banyak orang. Namun, dengan mengandalkan satu migran dan GPS, kursus kilat dalam navigasi laut, ban mobil untuk sekoci, dan terkadang bensin encer, risiko bagi penumpang sendiri sangat besar.

Sedikit simpati
Di bawah bayang-bayang pusat perbelanjaan tradisional kota, medina, seorang pemuda berusia 17 tahun – yang dengan seringai menyebut namanya sebagai Zidan Chouchen – bekerja di kios yang dia rawat setiap hari saat memasuki kota. Dia berkata dengan bangga bahwa penghasilannya hampir cukup untuk membayar perjalanannya sendiri yang tidak teratur ke Eropa.
Namun demikian, terlepas dari keadaan khususnya, dia memiliki sedikit simpati untuk para migran Afrika yang tidak berdokumen di kotanya.
“Kamu sewa rumah untuk dua orang, lalu mereka bawa teman, terus teman lagi,” ujarnya. “Mereka segera tidur di atap dan para tetangga mengeluh.
“Bagi kami, ketika kami pergi ke Eropa, kami memiliki tujuan: menyewa rumah dan membangun kehidupan baru. Bagi mereka, ketika datang ke sini, mereka hanya ingin mulai berkelahi, mengambil uang, dan bertindak seperti gangster. Sekarang mereka membunuh orang,” katanya.
Tidak mungkin Chouchen harus melakukan perjalanan dengan perahu logam. Kemungkinan penyeberangannya akan dilakukan di atas perahu kayu dengan nakhoda yang dikenal baik olehnya, keluarganya, atau teman-temannya. Bahkan yang putus asa memiliki sistem kelas mereka sendiri.

‘Datang untuk pekerjaan mereka’
Retorika resmi tentang krisis di Sfax meningkat. Pada hari Rabu, ketua parlemen, Brahim Bouderbala, dipanggil Presiden Saied turun tangan untuk “menyelamatkan” Sfax dari masuknya migran tidak berdokumen yang mengancamnya.
Delegasi dari petugas keamanan senior dikirim ke kota untuk membantu mengatasi situasi yang Saied sendiri gambarkan sebagai “abnormal“, bahkan jika seseorang terlibat dalam jenis pemikiran konspirasi yang telah menjadi ciri sebagian besar pandangan dunia presiden.
Meskipun banyak migran Afrika yang tidak berdokumen di Sfax bersiap untuk pemindahan paksa lebih lanjut, nuansanya tetap ada.
“Semua migran sub-Sahara yang datang ke kafe saya dan yang saya temui baik-baik saja,” kata pemilik kedai kopi Nadhem Trigi kepada Al Jazeera. “Mereka datang ke sini tanpa membawa apa-apa dan seringkali harus tinggal di lingkungan (kelas pekerja).”
Trigi mengatakan, meski sebagian besar kekerasan berasal dari rekan senegaranya, belum tentu soal rasisme.
“Mereka khawatir para migran datang ke selatan Sahara untuk uang mereka, pekerjaan mereka. Mereka khawatir seseorang datang ke tempat mereka dan mengambil milik mereka,” katanya. “Kita sudah berada dalam krisis ekonomi. Tidak ada makanan di pasar. Begitulah reaksi orang.”
Di Tunisia, Sfax identik dengan ketegangan rasial. Tapi untuk para pembuat kebijakan Eropa, yang saat ini bersiap untuk membayar lebih 1 miliar euro ($ 1,1 miliar) dalam bentuk bantuan, kota ini mewakili lebih banyak lagi.
Sementara detail pasti dari kesepakatan itu – dan apa yang mungkin ditawarkan Tunisia sebagai imbalannya – tetap tidak diketahui, prospek untuk bekerja dengan presiden garis keras negara itu – dan masyarakat yang terperosok dalam krisis ekonomi – tantangan juga tidak dapat disangkal.