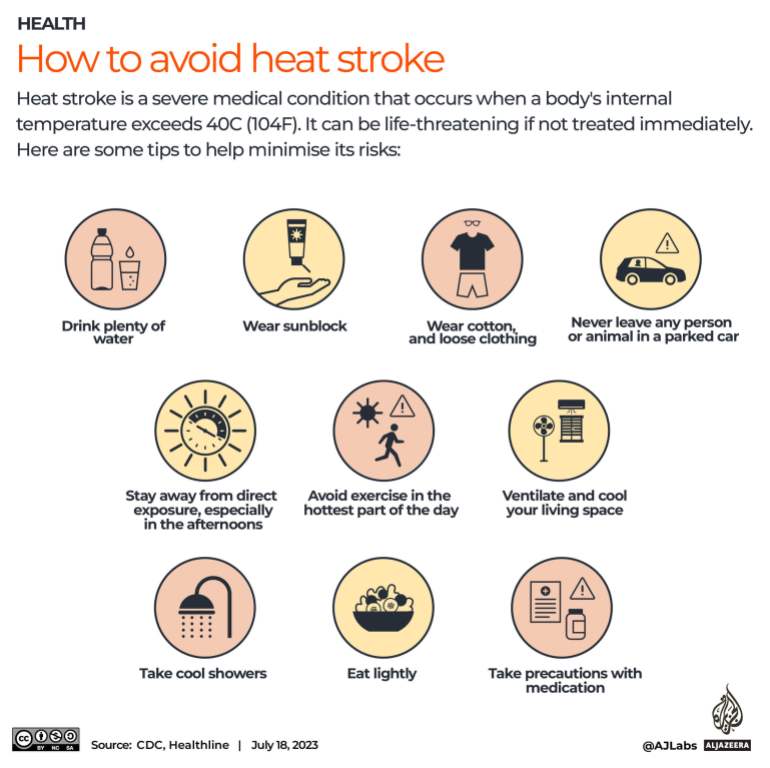Sudah hampir dua tahun sejak Taliban mengambil alih Kabul. Saya, seperti banyak orang Afghanistan yang telah bekerja keras untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berjuang. Pengetahuan tampaknya kehilangan nilainya dan buku tidak lagi dianggap sebagai milik yang berharga.
Ketika pejuang Taliban tiba di ibu kota Afghanistan pada Agustus 2021, banyak teman saya bergegas ke bandara untuk mencoba pergi, karena tidak melihat prospek bagi diri mereka sendiri di tanah air mereka. Pengurasan otak sangat besar.
Orang-orang dengan gelar master, PhD, dengan banyak buku yang diterbitkan, profesor, pendidik, dokter medis, insinyur, ilmuwan, penulis, penyair, pelukis – banyak orang terpelajar melarikan diri. Rekan saya – Alireza Ahmadi, yang bekerja sebagai reporter – juga ikut berdesak-desakan di bandara.
Sebelum dia pergi, dia menulis di halaman Facebooknya bahwa dia menjual 60 bukunya tentang berbagai topik untuk 50 orang Afghanistan (kurang dari $1). Dia tidak pernah berhasil keluar negeri; dia terbunuh dalam pengeboman bandara oleh Negara Islam di provinsi Khorasan.
Saya juga telah memutuskan untuk memberikan semua buku saya – semuanya 300 ratus buku, mencakup topik-topik seperti hukum internasional, hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan bahasa Inggris. Saya menyumbangkannya ke perpustakaan umum, berpikir bahwa di negara yang diperintah oleh Taliban, itu tidak ada nilainya bagi saya.
Saya mulai mencari cara untuk meninggalkan negara itu. Evakuasi bukanlah pilihan bagi saya, jadi saya memutuskan untuk pergi ke Iran, berharap bisa menemukan tempat berlindung yang aman di sana seperti jutaan warga Afghanistan lainnya. Tapi seperti rekan senegaraku, aku menghadapi penghinaan dan permusuhan di sana. Saya segera kehilangan semua harapan bahwa saya akan dapat mencari nafkah di Iran. Tapi saya menemukan sesuatu yang membuat saya terus maju – kecintaan lama saya pada buku.
Suatu hari, saat berjalan di sepanjang Alun-alun Enqelab di Teheran, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memasuki toko bukunya. Saya akhirnya menghabiskan sebagian besar dari sedikit uang yang saya miliki untuk buku-buku tentang hak asasi manusia dan hak-hak perempuan yang belum pernah saya lihat di Afghanistan. Berbekal buku-buku ini, saya memutuskan untuk kembali ke rumah dan mencoba kembali ke cara hidup lama saya – dikelilingi oleh buku-buku dan terlibat dalam pengejaran intelektual.
Sekembalinya, saya mulai mengerjakan sebuah buku tentang hak-hak politik perempuan dalam sistem hukum internasional dan dalam Islam, yang berhasil saya selesaikan dalam waktu sekitar satu tahun. Saya mengirim manuskrip saya ke penerbit yang berbeda tetapi berulang kali ditolak karena mereka menganggap subjeknya terlalu sensitif dan berpikir tidak mungkin mendapatkan izin untuk menerbitkannya.
Akhirnya, Ali Kohistani dari Mother Press setuju untuk mengambil buku tersebut. Dia menyiapkan dokumentasi yang diperlukan dan menyerahkan manuskrip tersebut ke Kementerian Informasi dan Kebudayaan Taliban untuk meminta izin resmi untuk menerbitkan. Segera setelah itu, panitia resensi buku mengirimi saya daftar panjang pertanyaan dan kritik yang perlu saya sampaikan.
Saya meninjau buku tersebut beserta umpan balik yang mereka kirimkan, tetapi itu tidak cukup untuk mendapatkan izin. Sekarang sudah lima bulan kami menunggu jawaban akhir dan keputusasaan saya tumbuh dari hari ke hari.
Kohistani telah berkali-kali pergi ke kementerian untuk menanyakan tentang manuskrip itu, tanpa hasil. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki lima buku lain yang ingin dia terbitkan tahun ini, tetapi belum ada yang disetujui oleh kementerian.
Penerbit lain juga menderita karena keputusan komisi yang sewenang-wenang dan penundaan yang lama. Mereka mengatakan buku-buku yang ingin diterbitkan oleh Taliban dan yang termasuk dalam ideologi mereka tidak menghadapi tantangan yang sama. Mereka melihat dalam proses yang rumit ini sebagai upaya untuk menekan setiap pemikiran yang tidak sejalan dengan pemikiran Taliban.
Penundaan izin dan penyensoran bukanlah satu-satunya masalah yang dialami industri buku Afghanistan.
Banyak toko buku dan penerbit tutup dalam dua tahun terakhir. Di kompleks buku di kawasan Pul-e-Surkh Kabul, yang sering saya kunjungi sebelum pengambilalihan Taliban, sebagian besar toko buku kini tutup.
Keputusan Taliban untuk melarang anak perempuan dan perempuan menghadiri sekolah menengah dan universitas berarti mereka tidak lagi membeli banyak buku. Anak laki-laki dan laki-laki muda juga telah meninggalkan sekolah dan universitas, karena mereka kehilangan motivasi untuk mengikuti pendidikan yang tidak dapat menjamin mereka mendapatkan pekerjaan. Ini sangat menyusutkan basis pelanggan penjual buku.
Selain itu, pemerintah Taliban memberlakukan pajak yang tinggi atas penjualan buku, yang selanjutnya mengurangi penurunan pendapatan pemilik dan penerbit toko buku.
Perpustakaan di seluruh negeri juga kehilangan pembacanya karena semakin sedikit orang yang pergi ke sana untuk belajar atau meminjam buku. Beberapa klub buku, asosiasi sastra, dan inisiatif membaca juga menghentikan kegiatannya. Tidak lagi dipandang sebagai nilai untuk memiliki, membaca, atau menulis buku.
Dalam semalam, penerbitan buku Afghanistan berubah dari sektor yang berkembang pesat – mungkin industri rumahan yang paling sukses – menjadi usaha bisnis yang sulit dan berisiko. Orang-orang Afghanistan telah berubah dari gemar membaca menjadi tidak mampu membeli buku. Saya beralih dari seorang penulis dan pemilik buku yang bangga menjadi seorang pria putus asa yang mencoba dan gagal mempertahankan kehidupan intelektual di Afghanistan.
Sangat menyakitkan melihat keadaan ini di Afghanistan – sebuah negara dengan sejarah dan tradisi sastra yang panjang. Negara ini memberi dunia orang-orang seperti Jalal ad-Din Muhammad Balkhi (alias Rumi), Ibn Sina Balkhi (alias Avicenna) dan Hakim Sanai Ghaznavi (alias Sanai).
Membaca, menulis, dan menyebarkan pengetahuan selalu dihargai tinggi di negara saya. Penguasa Afghanistan dari berbagai dinasti menghormati kebebasan berpikir dan mendukung pembelajaran dan produksi pengetahuan. Penyensoran, pembatasan pendidikan dan devaluasi buku tidak pernah menjadi bagian dari tradisi atau budaya Afghanistan.
Tidak ada negara dalam sejarah dunia yang pernah makmur ketika penguasanya menindas pengetahuan, pendidikan, dan kebebasan berpikir. Afghanistan bergerak menuju kegelapan dan ketidaktahuan dan itu membuatku takut. Membunuh buku dan membunuh ilmu akan berakibat fatal bagi masa depan negeri ini.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan posisi redaksi Al Jazeera.